“Kenapa sekarang kamu jarang terlihat jalan sama siapa-siapa?” tanya seorang teman sambil menyeruput kopi yang mulai dingin.
Aku tersenyum tipis. “Bukan kenapa-kenapa. Cuma merasa nggak perlu.”
Ia menatap sebentar, seolah menimbang jawabanku. “Padahal dulu, kamu gampang dekat sama siapa pun.”
ADVERTISEMENT
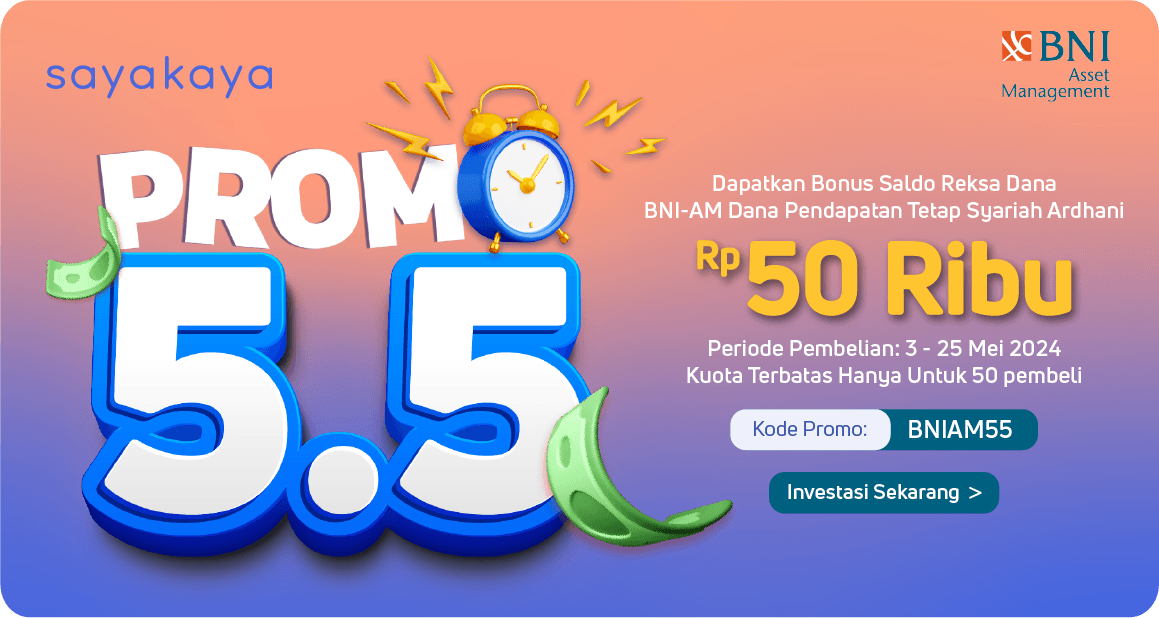 .
.SCROLL TO RESUME CONTENT
Aku mengangguk pelan. Dulu memang begitu. Perhatian datang tanpa dicari. Pergaulan kampus, rasa percaya diri, dan usia muda membuat semuanya terasa mudah. Pacaran, jalan berdua, nongkrong sampai malam, semua pernah dilewati. Tapi entah sejak kapan, ada rasa kosong yang muncul, tanpa sebab yang jelas.
“Capek?” ia kembali bertanya.
“Mungkin,” jawabku. “Atau mungkin aku mulai sadar, nggak semua yang terlihat menyenangkan itu benar-benar penting.”
Aku terdiam sejenak. Dalam hati, pertanyaan itu sering datang sendiri. Waktu terasa habis begitu saja. Pikiran penuh, tapi tujuan hidup justru makin kabur. Banyak hal berputar di fisik dan tampilan luar, tapi sedikit yang benar-benar menyentuh hati.
“Terus sekarang?” katanya lagi.
“Aku berhenti,” jawabku jujur. “Bukan karena nggak bisa, tapi karena pengin jaga diri.”
Keinginan itu tentu masih ada. Ketertarikan pada rupa, pada fisik, adalah hal yang wajar. Tapi semakin ke sini, aku belajar bahwa perempuan bukan sekadar tentang penampilan. Yang bertahan lama justru hati, cara bersikap, dan ketulusan. Fisik bisa menarik, tapi hati yang menenangkan jauh lebih berharga.
Aku mulai mengalihkan fokus pada hal yang lebih nyata: belajar, bekerja, dan berusaha membahagiakan orang tua. Dari situ, hidup terasa lebih terarah. Ada capek, tapi juga ada tenang.
“Aku juga sempat masuk ke dunia anonim,” lanjutku pelan. “Bukan buat cari siapa-siapa, tapi buat belajar memahami.”
Di ruang tanpa nama dan wajah, aku mengamati cara orang berbicara. Dari kalimat sederhana, respons jujur, hingga sikap yang kadang tiba-tiba menghilang. Banyak pertemanan hanya bertahan singkat. Satu bulan, dua bulan, lalu selesai tanpa penjelasan.
“Dan kamu nggak kecewa?” tanyanya.
“Awalnya iya,” kataku. “Tapi lama-lama aku paham.”
Tidak semua orang datang untuk menetap. Ada yang hadir hanya untuk memberi pelajaran. Namun sesekali, muncul sosok yang berbeda. Bukan karena cantik atau menarik secara fisik, melainkan karena sikapnya yang tenang, ucapannya yang dijaga, dan hatinya yang terasa tulus meski hanya lewat kata-kata.
“Ada yang bikin kamu berubah?” ia tersenyum kecil.
“Ada yang bikin aku mengerti,” jawabku. “Bahwa memahami perempuan itu bukan soal memiliki, tapi menghargai. Bukan soal rupa, tapi hati.”
Aku menatap keluar jendela. Hujan turun perlahan, membuat suasana semakin sunyi.
“Aku yakin,” kataku pelan, “suatu hari nanti aku akan jadi suami. Dan bekalku bukan dari banyaknya hubungan, tapi dari cara memandang perempuan dengan lebih dewasa, lebih manusiawi, dan lebih jujur.”
Temanku mengangguk. “Sekarang kamu kelihatan lebih tenang.”
Aku tersenyum. Karena memang begitu rasanya. Pada akhirnya, yang paling berharga bukan cahaya dari fisik yang mudah pudar, melainkan cahaya dari hati yang mampu bertahan dalam waktu.














